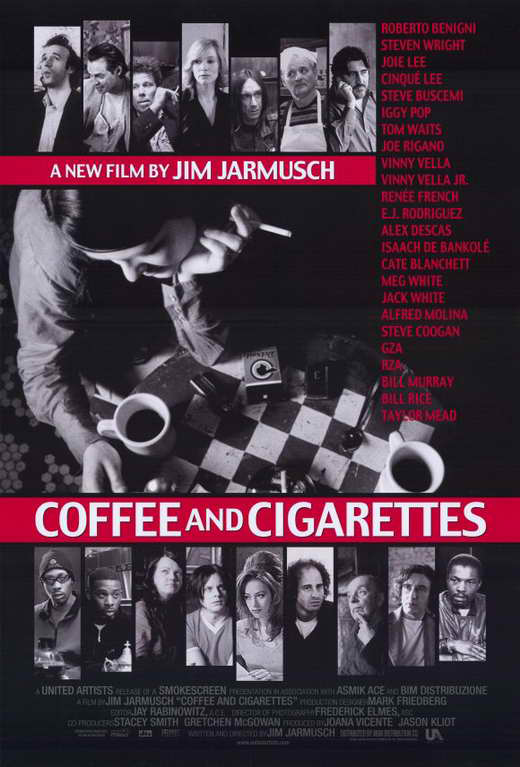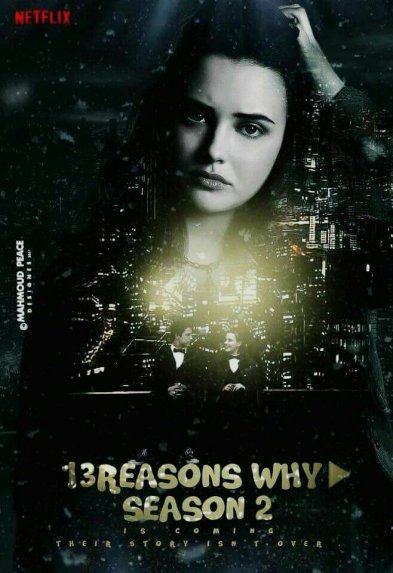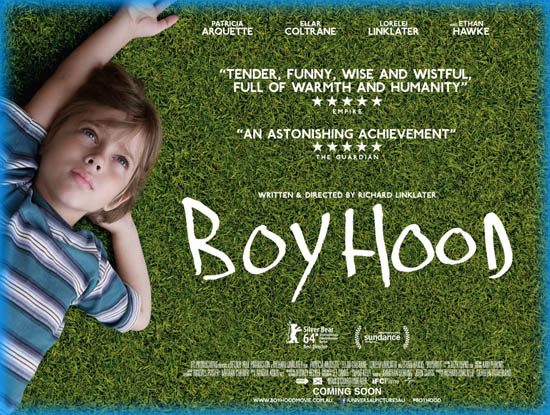Sudah lama saya berbohong pada diri sendiri. Tanpa disadari sama sekali. Tak tahu berapa lama tepatnya. Bahwa saya sebenarnya tidak baik-baik saja.
Bukan dalam artian untuk menempatkan diri jadi manusia paling menderita sedunia dan membuat saya pribadi jadi pusat kejadian alam raya. Semua orang punya lukanya masing-masing dan setelah tamat menonton drama korea satu ini, luka saya menganga sangat lebar. Entah luka yang mana, hanya rasa sakitnya saja yang jelas terasa.
Terlambat sebetulnya saya menonton Itaewon Class ini, kalau dibandingkan teman-teman yang sudah lebih dulu menamatkannya. Kebetulan pula saya baru saja membaca sebuah artikel di bacapetra.co berupa sebuah esai dari Stefano Benni yang sudah diterjemahkan. Dalam esai tersebut ia menceritakan seorang bernama Roberto Roversi. Dalam esai tersebut, Roberto berkata bahwa, “buku-buku memilih siapa yang ingin membeli mereka”. Dalam sebuah konteks, saya mengartikannya sebagai buku memilih siapa yang membacanya, bukan orang yang memilih untuk membaca buku apa.
Mungkin di sini saya juga tidak memilih untuk secara sadar untuk menonton telenovela dari Korea ini, melainkan saya memilih untuk dipilih oleh karya tersebut untuk menyerap cerita-cerita dan segala konflik yang ada di dalamnya. Hahaha. Saya tidak bisa dipilih begitu saja oleh hal yang ada di luar saya secara sepihak. Saya pun memiliki hak dalam memilih untuk dipilih.
Saya tertarik dengan serial ini karena menurut sebuah selentingan kabar, serial ini mengisahkan konflik bisnis di dalamnya. Saya yang masih memiliki minat dalam dunia bisnis, tentunya menjadi penasaran dan ingin belajar santai dari apa-apa yang terdapat di dalamnya. Dan berdasarkan sebuah penuturan teman, saya diharapkan untuk tidak memiliki ekspektasi tinggi bila memang itu jadi alasannya, karena tidak begitu dalam membahas bisnis.
Well, perkataan teman saya benar. Saya yang tidak mencari-cari tahu lebih jauh ulasan di luaran sana menuruti keinginan dia dengan tetap berusaha akan menikmati waktu saya dalam menontonnya. Bagi yang belum menonton serial ini, perkenankan saya untuk merangkum satu season Itaewon Class dalam sebuah premis cerita. Itaewon Class ini adalah sebuah kisah dari tokoh bernama Park Saeroyi yang ingin membalaskan dendam kepada sebuah perusahaan makanan bernama Jangga.Co, namun di tengah jalan ia dihadapkan pada kekuatan yang sangat besar dari lawannya tersebut dan terlibat dalam konflik cinta segi empat bersama cinta pertamanya semasa sekolah dulu dan pegawainya di perusahaan yang sedang ia bangun.
Pengalaman menonton serial biasanya dilakukan dengan cara marathon menonton setiap episodenya. Saya berusaha menahan hal demikian karena terkait dengan kegiatan lain dalam kehidupan manusia, hehe. Dengan metode itu, saya biasa menontonnya pada malam hari, sebagai pengantar tidur di waktu yang sepi dan sudah gelap. Keputusan saya ternyata salah. Betul-betul salah.
Ada sebuah perkataan yang berbunyi “Berhati-hatilah terhadap mulutmu ketika bersama orang lain, dan berhati-hatilah terhadap pikiranmu ketika kamu sendiri”. Pertahanan saya lengah karena ketidak hati-hatian tersebut. Waktu malam adalah waktu tersunyi yang dimiliki manusia, yang sering digunakan untuk menenangkan pikiran, mencari inspirasi, atau bahkan melakukan refleksi pada apa yang telah terjadi. Waktu menonton yang sering dilaksanakan di atas pukul 10 malam ini justru mengacak-acak perasaan saya melalui pikiran yang semakin liar setiap beres menonton satu episode.
Tidak pernah ada satu warna rasa apalagi rasa tunggal yang muncul ketika beres menonton episode tiap episode. Selalu ada perasaan heart-warming sekaligus kekosongan, ada rasa bangga sekaligus kecewa, selalu ada api semangat yang bisa muncul tiba-tiba sekaligus ditemani perasaan putus asa. Semua muncul di saat bersamaan, tidak pernah saling bergantian. Pengalaman itulah yang selalu mengacak-acak saya ini. Serumit itu yang saya rasakan.
Itaewon Class tidak hanya sebuah tontonan bagi saya. Ia adalah sebuah pengalaman yang buat saya sendiri bisa disikapi sebagai sebuah pengalaman berharga. Sudah lama saya tidak merasakan emosi yang diaduk-aduk seperti ini.
Saya pun ingin memberi hormat setinggi-tingginya kepada pemilihan lagu latar dalam serial ini. Nomer-nomer lagu yang diputar di sini begitu menghidupkan suasana dan membawa emosi luar biasa. Walaupun hampir semuanya berbahasa Korea yang sama sekali saya tidak mengerti, tapi lagu-lagu “bernuansa minor” ini menusuk dada saya di setiap penggalan adegan yang dipasang begitu tepat. Menyimpan beban berat dalam paru-paru sehingga napas saya menjadi lebih pendek setiap saya menonton ini.
Pengalaman-pengalaman menonton tersebut yang akhirnya membuat pertahanan yang saya bangun runtuh seketika selepas tamat menonton Itaewon Class. Ada dua lagu tambahan yang bisa membuat saya tidak karuan selepas mendengarnya sekarang. Dua lagu itu didapat dari drama ini. Dua lagu itu adalah berjudul ‘Someday, The Boy’ dan ‘Still Fighting It’.
Melalui dua lagu itu, saya sadar saya sedang berada dalam keadaan tidak baik-baik saja. Berdasarkan pada apa yang sedang saya alami sekaligus apa yang saya lakukan sehari-hari. Pertanyaan-pertanyaan dasar sebagai bahan bakar hidup kembali menyeruak, membuka mata saya kembali bahwa banyak yang harus saya lakukan dan berikan pada orang di sekitar saya yang belum bisa saya penuhi. Pertanyaan macam ‘Apa tujuan kamu?’, ‘Bagaimana kamu ingin menjalani ini semua?’, ‘Kenapa kamu melakukan ini?’, dan sejawatnya muncul kembali.
Ketika pertanyaan itu muncul, saya tertampar oleh diri sendiri, bahwa saya tengah kehilangan diri saya sendiri. Saya jauh dari diri saya sendiri. Dan itu sangat menyakitkan, setidaknya bagi saya. Kepedihan yang sangat menyedihkan, mungkin? Bisa jadi.
Pada saat saya mendengarkan lagu tersebut, saya tidak mengerti artinya sama sekali karena yang satu mengandung lirik berbahasa Korea yang saya tidak paham sama sekali dan yang satu lagi saya tidak mendengarkan nyanyian sebagai sebuah vokal yang mengandung lirik, melainkan sebuah instrumen saja seperti alat musik lain seperti piano. Bisa dibayangkan bagaimana sembabnya mata setiap hari bila harus menguras emosi akibat lirik yang terkandung dalam kedua lagu tersebut yang segera saya pahami maknanya seketika saya menonton episode demi episode.
Saya coba memainkan kedua lagu tersebut pada sebuah keyboard dingin yang sangat jarang tersentuh. Begitu saya memainkannya, lebih dalam saya larut dalam perasaan. Pecah tangis sejadi-jadinya setelah memainkannya beberapa kali. Bukan karena cerita dalam Itaewon Class yang bersisa dan meninggalkan kesan, melainkan pada bayangan masa lalu yang tak bisa diubah lagi.
Kalau saya bisa, ingin sekali bisa membuat diri menjadi dua. Melontarkan kata makian sebanyak-banyak pada orang yang ada di hadapan saya itu, bertanya banyak hal, mendengarkan jawaban, dan diakhiri dengan sebuah pelukan hangat. Setelah itu kami tersenyum sebagai simbol sebuah gencatan senjata dan kesepakatan baru.
Apa yang telah saya lakukan rasanya seakan tidak cukup baik saat ini. Pelajaran dan pengalaman yang telah didapat sangat tidak cukup. Saya masih harus berusaha memperbaiki banyak aspek dalam hidup. Lebih keras, lebih cerdas, lebih ikhlas. Klise. Tapi, mungkin memang itu jawabannya. Siapa yang tahu?
Apakah serial ini bisa dikatakan mengubah hidup saya? Biarkan waktu yang menjawab, ditemani oleh saya yang mencari tahu.